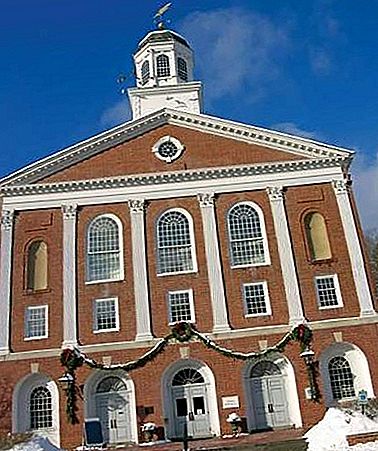Keabadian, dalam falsafah dan agama, kesinambungan keberadaan mental, rohani, atau fizikal individu manusia. Dalam banyak tradisi falsafah dan agama, keabadian secara khusus dianggap sebagai keberadaan jiwa atau fikiran yang tidak material di luar kematian fizikal tubuh.

Kekristianan: Kekekalan jiwa
Manusia nampaknya selalu mempunyai tanggapan tentang bayangan berganda yang bertahan dari kematian mayat. Tetapi idea jiwa sebagai
Ahli antropologi terdahulu, seperti Sir Edward Burnett Tylor dan Sir James George Frazer, mengumpulkan bukti yang meyakinkan bahawa kepercayaan pada kehidupan masa depan tersebar luas di wilayah budaya primitif. Di antara kebanyakan orang kepercayaan ini berterusan selama berabad-abad. Tetapi sifat keberadaan masa depan telah disusun dengan cara yang sangat berbeza. Seperti yang ditunjukkan oleh Tylor, pada masa yang paling awal diketahui terdapat hubungan etika yang kecil, sering kali tidak ada, antara tingkah laku di bumi dan kehidupan di luar. Morris Jastrow menulis mengenai "ketiadaan hampir semua pertimbangan etika yang berkaitan dengan orang mati" di Babylonia kuno dan Asyur.
Di beberapa wilayah dan tradisi keagamaan awal, dinyatakan bahwa para pejuang yang mati dalam pertempuran pergi ke tempat kebahagiaan. Kemudian ada perkembangan umum idea etika bahawa akhirat akan menjadi hadiah dan hukuman atas tingkah laku di bumi. Oleh itu, di Mesir kuno semasa kematian, individu tersebut dilantik sebagai pengadilan yang datang ke hadapan hakim. Pengikut Parsi Zoroaster menerima pengertian Chinvat peretu, atau Jambatan Pemohon, yang harus dilintasi setelah mati dan luas bagi orang benar dan sempit bagi orang fasik, yang jatuh dari neraka. Dalam falsafah dan agama India, langkah ke atas - atau ke bawah - dalam rangkaian kehidupan yang menjelma di masa depan telah (dan masih) dianggap sebagai akibat dari tingkah laku dan sikap dalam kehidupan sekarang (lihat karma). Idea mengenai ganjaran dan hukuman di masa depan disebarkan di kalangan orang Kristian pada Zaman Pertengahan dan dipegang pada masa ini oleh banyak orang Kristian dari semua denominasi. Sebaliknya, banyak pemikir sekular berpendapat bahawa kebaikan moral harus dicari untuk dirinya sendiri dan kejahatan dijauhi sendiri, terlepas dari kepercayaan apa pun dalam kehidupan masa depan.
Bahawa kepercayaan terhadap keabadian telah tersebar luas sepanjang sejarah bukanlah bukti kebenarannya. Ini mungkin takhayul yang timbul dari mimpi atau pengalaman semula jadi yang lain. Oleh itu, persoalan mengenai kesahihannya telah diajukan secara filosofis sejak awal bahawa orang mula terlibat dalam refleksi cerdas. Dalam Hindu Katha Upanishad, Naciketas mengatakan: “Keraguan ini ada mengenai seorang lelaki yang ditinggalkan — ada yang mengatakan: Dia; sebilangan: Dia tidak wujud. Saya tahu ini. " Upanishad - asas kebanyakan falsafah tradisional di India - terutama merupakan perbincangan mengenai hakikat kemanusiaan dan tujuan utamanya.
Keabadian juga merupakan salah satu masalah utama pemikiran Plato. Dengan anggapan bahawa kenyataan, pada hakikatnya, bersifat spiritual, dia berusaha membuktikan keabadian, dengan menyatakan bahawa tidak ada yang dapat menghancurkan jiwa. Aristoteles menganggap akal sebagai abadi tetapi tidak mempertahankan keabadian peribadi, kerana dia berpendapat jiwa itu tidak dapat wujud dalam keadaan tidak berhias. Orang-orang Epicurean, dari sudut pandang materialistik, berpendapat bahawa tidak ada kesadaran setelah mati, dan dengan demikian tidak perlu ditakuti. The Stoics percaya bahawa ia adalah alam semesta yang rasional secara keseluruhan yang berterusan. Manusia secara individu, seperti yang ditulis oleh maharaja Rom Marcus Aurelius, mempunyai masa yang diperuntukkan dalam drama keberadaan. Namun, orator Rom Cicero akhirnya menerima keabadian peribadi. St. Augustine of Hippo, mengikuti Neoplatonisme, menganggap jiwa manusia sebagai hakikatnya kekal.
Ahli falsafah Islam Avicenna mengisytiharkan jiwa itu abadi, tetapi ahli agamanya, Averroës, yang tetap dekat dengan Aristoteles, hanya menerima keabadian hanya sebab universal. St. Albertus Magnus mempertahankan keabadian dengan alasan bahawa jiwa, dengan sendirinya menjadi penyebab, adalah kenyataan yang bebas. John Scotus Erigena berpendapat bahawa keabadian peribadi tidak dapat dibuktikan atau dibantah oleh akal. Benedict de Spinoza, menganggap Tuhan sebagai kenyataan hakiki, secara keseluruhan mempertahankan kekekalannya tetapi bukan keabadian individu-individu di dalam dirinya. Ahli falsafah Jerman Gottfried Wilhelm Leibniz berpendapat bahawa realiti terdiri daripada monad spiritual. Manusia, sebagai monad yang terbatas, tidak dapat berasal dari komposisi, diciptakan oleh Tuhan, yang juga dapat memusnahkannya. Namun, kerana Tuhan telah menanamkan pada manusia perjuangan untuk kesempurnaan rohani, mungkin ada keyakinan bahwa Dia akan memastikan keberadaan mereka terus-menerus, sehingga memberi mereka kemungkinan untuk mencapainya.
Ahli matematik dan ahli falsafah Perancis Blaise Pascal berpendapat bahawa kepercayaan kepada Tuhan Kekristenan - dan sesuai dengan keabadian jiwa - dibenarkan berdasarkan alasan praktikal oleh fakta bahawa orang yang percaya mempunyai segalanya untuk memperoleh jika dia benar dan tidak ada yang hilang jika dia salah, sementara orang yang tidak percaya akan kehilangan segalanya jika dia salah dan tidak akan mendapat apa-apa jika dia betul. Ahli falsafah Pencerahan Jerman Immanuel Kant berpendapat bahawa keabadian tidak dapat ditunjukkan dengan alasan murni tetapi harus diterima sebagai syarat penting moral. Kekudusan, "sesuai dengan kehendak yang sesuai dengan hukum moral," menuntut kemajuan yang tidak berkesudahan "hanya mungkin dengan andaian jangka masa yang tidak berkesudahan dari keberadaan dan keperibadian makhluk yang sama rasionalnya (yang disebut keabadian jiwa)." Hujah yang jauh lebih canggih sebelum dan sesudah Kant berusaha untuk menunjukkan realiti jiwa yang tidak kekal dengan menegaskan bahawa manusia tidak akan mempunyai motivasi untuk bersikap moral kecuali mereka percaya pada akhirat yang kekal di mana kebaikan dibalas dan kejahatan dihukum. Hujah yang berkaitan menyatakan bahawa menolak pahala dan hukuman akhirat yang kekal akan membawa kepada kesimpulan yang menjijikkan bahawa alam semesta itu tidak adil.
Pada akhir abad ke-19, konsep keabadian merosot sebagai keasyikan falsafah, sebahagiannya kerana sekularisasi falsafah di bawah pengaruh sains yang semakin meningkat.